Kewargaan Pascakolonial di Provinsi Indonesia
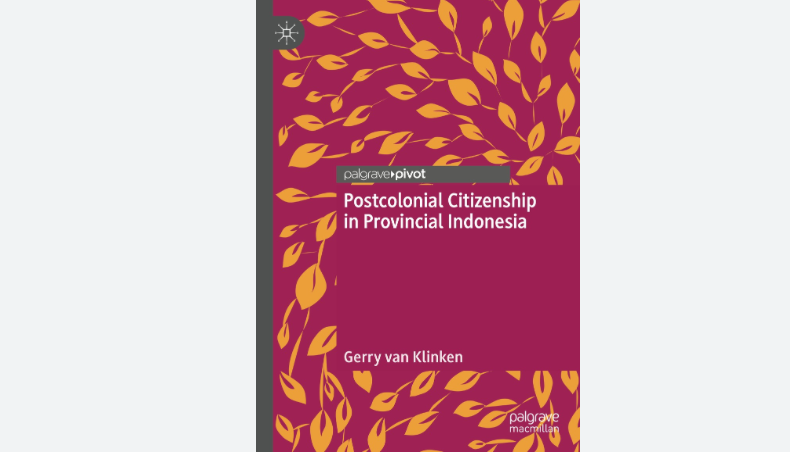
Buku ini dimulai dengan kisah Jan Djong , putra seorang mantan kepala desa dan petani di sebuah desa bernama Hewokloang di tenggara Maumere , Nusa Tenggara Timur. Kisah Djong dimulai dengan kematiannya yang mengerikan pada tahun 1966. Setelah ditahan pada awal tahun itu, ia dipukuli, diarak keliling kota, dikencingi, dibunuh tanpa diadili, dan dikubur di tepi sungai di luar penjara. Peristiwa-peristiwa sebelumnya memberikan gambaran yang sama sekali berbeda tentang Jan Djong . Pada tahun 1953, ia menjadi orang di balik demonstrasi pertama di Maumere , yang terdiri dari petani subsisten, yang secara terbuka menyatakan kebencian mereka terhadap Raja (penguasa lokal). “Di mana ada raja = di situ ada kolonialisme”, baca salah satu tanda yang terbuat dari tikar daun kelapa dan dicat dengan cat putih.
Selama tahun itu, Djong adalah tokoh lokal dari gerakan anti-feodalisme dan anti-kolonialisme di Republik Indonesia yang baru. Sungguh aneh, dan memilukan, melihat pria ini bertransformasi dari seorang agitator anti-kolonial di awal kemerdekaan Indonesia menjadi korban pembunuhan massal nasional dalam kekerasan anti-komunis 1965–1966. Namun, hal ini justru berpusat pada pertanyaan utama yang ingin diangkat oleh Gerry van Klinken : mengapa Indonesia sebagai sebuah bangsa bergerak begitu cepat dari harapan tinggi menuju pembunuhan massal? (hlm. 4). Jawabannya terletak pada analisis kewarganegaraan, yang diperkenalkan van Klinken secara tepat dan kritis kepada para pembacanya melalui kisah Djong .
Peristiwa yang terjadi di kota provinsi Maumere juga bergema di belahan dunia lain, terutama negara-negara dengan perjuangan pascakolonial. Van Klinken menunjukkan bahwa teori kewarganegaraan konvensional tidak cukup untuk memahami cerita yang mirip dengan Jan Djong . Teori-teori tersebut menampilkan asumsi dasar bahwa ada negara yang kuat yang akan (dan harus) menjamin hak-hak warga negaranya. Dalam banyak konteks pascakolonial, hal ini tidak terjadi dengan mulus. Negara-negara seperti itu dengan mudah dikategorikan sebagai rendah dalam ‘aturan hukum’ (hlm. 12). Konsepsi yang menunjukkan gambaran ideal warga negara yang menuntut hak cenderung menyederhanakan perjuangan dekolonisasi dan demokratisasi hanya sebagai kekerasan, perpecahan, atau kekacauan di negara berkembang. Van Klinken kemudian beralih ke teori kewarganegaraan kritis lainnya yang berasal dari konteks pascakolonial, dari Partha Chatterjee hingga Mahmood Mamdani dan Catherine Boone, yang menekankan peran pemerintahan tidak langsung dan dinamika antara elit pusat dan daerah.
Dengan menggunakan dua teks lokal sebagai sumber sejarah (satu oleh penduduk lokal dan yang lainnya oleh seorang pendeta asing), van Klinken berhasil menulis catatan rinci tentang kota provinsi Maumere dengan Djong sebagai protagonis, sambil menempatkannya dalam sejarah pembentukan negara Indonesia. Salah satu bagian awal dari pembentukan negara ini terdiri dari kolonialisme Belanda, yang memanfaatkan pemerintahan tidak langsung para Raja di pulau itu. Sebagai imbalannya, para Raja tersebut menikmati dukungan kolonial yang mengamankan posisi mereka sebagai penguasa lokal dan birokrat kolonial, yang memungkinkan mereka untuk mengenakan pajak kepada penduduk desa atas produksi kelapa mereka. Ayah Jan Djong adalah salah satu kepala desa di Hewokloang , di Sikka, tetapi kemudian kehilangan pekerjaannya ketika desa tersebut terintegrasi di bawah kekuasaan Raja Sikka pada akhir tahun 1920-an. Yang terakhir memilih kerabatnya untuk menjadi pemimpin desa. Ini menjadi awal dari kebencian keluarga Djong terhadap para Raja. Kebencian ini memicu sebuah gerakan ketika negara kolonial di Sikka menjadi Republik Indonesia pada tahun 1949.
Jan Djong adalah bagian dari lingkaran penguasa semi-terpelajar. Di bawah Republik yang baru pada tahun 1950, ia diangkat sebagai anggota kabinet penasehat bupati Sikka. Sembari memegang jabatan ini, ia juga memobilisasi gerakan anti-feodal, memprotes keras pemungutan pajak oleh pejabat di daerah pedesaan. Hal ini tentu saja mencerminkan harapan Republik yang baru terbentuk: membuka lingkungan yang demokratis dan egaliter, dengan aspirasi yang ditumbuhkan dari bawah. Di sisi lain, negara pusat, dengan pesannya tentang kebebasan dari kolonialisme dan feodalisme, tidak berada dalam posisi untuk memaksakan aturan baru, maupun mengeluarkan dana baru untuk Sikka (hlm. 73). Hal ini mendorong warga untuk mengelola dan menegosiasikan pajak mereka sendiri, yang berasal dari dana kopra, dan diawasi oleh pemerintah daerah. Van Klinken menganggap hal ini sebagai republikanisme agonistik: perjuangan politik lokal beresonansi dengan “kebisingan” kontroversi nasional, tanpa sepenuhnya ditentukan olehnya (hlm. 73).
Klimaks cerita, yang juga menjadi argumen utama penulis, terletak pada bab 4. Di sini, penulis dengan cermat menggambarkan hubungan patronase atau klientelis yang terbentuk di Sikka—hubungan yang didasarkan pada ikatan personal, afektif, dan resiprokal (namun tidak setara) yang melibatkan transaksi yang saling menguntungkan (hlm. 80). Di Sikka, hubungan patronase terbentuk antara elit lokal dengan jaringan nasional dan klien lokal mereka, dipengaruhi oleh ekonomi kopra yang sedang booming. Dengan menjerat konektivitas berlapis ini, van Klinken pertama-tama berpendapat bahwa sejarah Kemerdekaan, seperti yang ditunjukkan dalam sejarah Maumere dan Sikka, menunjukkan kesinambungan dengan era kolonial. Bangsawan kolonial hanya digantikan (tidak berkurang) oleh patron non-bangsawan seperti pejabat, pengusaha, politisi, dan tokoh agama (hlm. 89). Alur penalaran kedua penulis, yang berfungsi sebagai kritik keras terhadap teori-teori kewarganegaraan etnosentris konvensional, berpendapat bahwa “negara sebagai sistem impersonal untuk mengalokasikan hak adalah sebuah fiksi” (hlm. 98). “Hak”, yang begitu sentral dalam teori kewarganegaraan, tidak secara otomatis terjamin. Bahkan ketika lembaga-lembaga untuk melindungi hak-hak warga negara ada, misalnya dalam bentuk majelis distrik atau penganiaya publik, lembaga-lembaga tersebut seringkali didominasi oleh patron elit. Oleh karena itu, upaya untuk menuntut hak dapat dilihat sebagai langkah-langkah personal untuk melawan individu atau kelompok yang superior.
Pendekatan patronase ini cukup menjelaskan mengapa warga sipil biasa terlibat dalam pembunuhan massal, di mana baik korban maupun pelaku sebagian besar saling mengenal. Tindakan kekerasan bukan sekadar pertunjukan kejahatan yang biasa, tetapi juga berfungsi sebagai tindakan transaksional. Para algojo mengikuti perintah militer karena utang faksi , menurut Mayor Soemarno , Komandan Garnisun Militer di Maumere dan Kepala Komando. Operasi . Dalam kasus ini, utang-utang ini merupakan utang kepada patron sebagai imbalan atas jaminan stabilitas ekonomi dan politik di Maumere . Kekerasan pada tahun 1965–1966 merupakan genosida yang menguntungkan kaum elite di kota (hlm. 118). Kekerasan ini memuncak setelah ketegangan yang berkepanjangan, dan terjalin dengan pergolakan nasional. Inilah dinamika yang paling berbahaya, menurut van Klinken : “fakta bahwa lembaga-lembaga negara pusat bersekutu dengan elite lokal yang anti-demokrasi, mengotorisasi dan memaksa mereka untuk membawa pertikaian faksional klientelis mereka ke tingkat kekerasan ekstrem” (hlm. 127–28).
Gerry van Klinken dengan brilian menyajikan sejarah mikro ini, baik sebagai kritik maupun kontribusi bagi bidang studi kewarganegaraan yang sedang berkembang pesat. Kasus Sikka merupakan ilustrasi konkret dari sebuah kontes kewarganegaraan, yang bertujuan untuk memperluas komunitas politik agar mencakup mereka yang terpinggirkan sejak masa kolonial (hlm. 137). Inilah kewarganegaraan di zona abu-abu, sebagaimana terlihat di sebagian besar negara pascakolonial. Pada akhirnya, van Klinken menunjukkan masa depan kewarganegaraan yang lebih menjanjikan, dengan pertumbuhan gerakan-gerakan rakyat dan “pembelajaran peradaban” yang sedang berlangsung. Masa depan mungkin tidak sesuram itu.

direview oleh Grace Leksana Gerry van Klinken , Kewarganegaraan Pascakolonial di Provinsi Indonesia . Singapura: Palgrave Macmillan, 2019, xvii + 152 hlm. ISBN : 9789811367243, harga: EUR 49,99 (sampul keras); 9789811367250, EUR 42,79 ( buku elektronik ). diterjemahkan dari https://brill.com/view/journals/bki/177/2-3/article-p432_22.xml?srsltid=AfmBOorLXiGLUTObaryAFWEqhNfZCt7nQTrwqbAdtHU9pIR3FFa0tVQn