Ketika Sungai dan Pohon Menuntut Hak: Belajar dari Buku ‘Understanding the Rights of Nature’
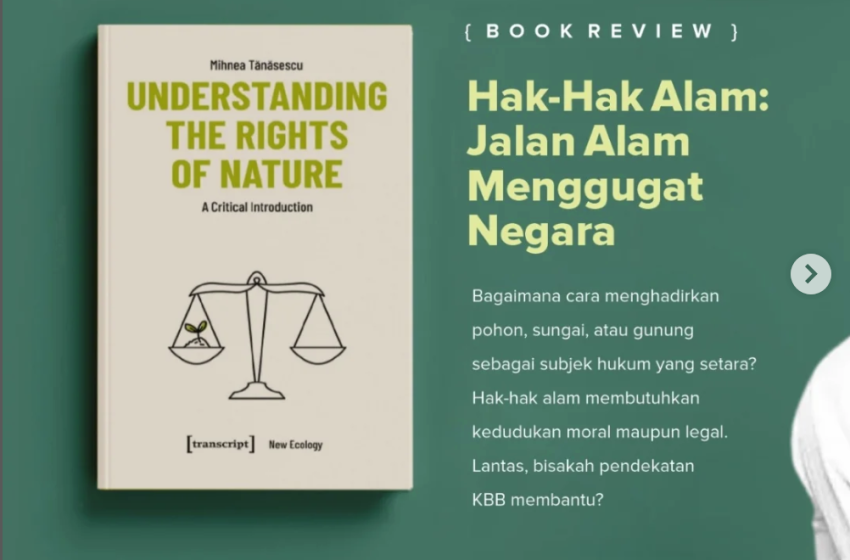
Bayangkan sebuah sungai. Airnya mengalir deras dari hulu, menyusuri lembah, membawa kehidupan bagi komunitas di sekitarnya. Lalu, suatu hari, sebuah perusahaan membangun pabrik dan membuang limbahnya ke aliran sungai itu. Air yang jernih menjadi keruh, ikan-ikan mati, dan warga pun jatuh sakit. Dalam sistem hukum kita yang berlaku, apa yang bisa kita lakukan?
Biasanya, kita akan menggugat perusahaan itu karena melanggar hak-hak manusia—hak untuk hidup sehat, hak atas lingkungan yang baik. Sungai itu sendiri, yang rusak dan tercemar, hanyalah objek dalam kasus hukum; properti yang dirusak. Tapi, bagaimana jika kita bisa membalikkan paradigma ini? Bagaimana jika sungai itu sendiri, sebagai entitas hidup, yang bisa menggugat di pengadilan untuk membela haknya untuk eksis, berkembang, dan beregenerasi?
Inilah gagasan radikal yang diusung oleh gerakan Rights of Nature (Hak-Hak Alam), dan inilah yang diteliti secara mendalam dan elegan oleh Mihnea Tănăsescu dalam bukunya yang monumental, “Understanding the Rights of Nature: A Critical Introduction” (2022). Buku ini bukan sekadar paparan teori, melainkan sebuah perjalanan filosofis dan politis yang menantang fondasi paling dasar dari sistem hukum modern: pemisahan mutlak antara subjek (manusia yang memiliki hak) dan objek (alam yang dimiliki).
Sebagai seorang filsuf politik, Tănăsescu tidak terjebak dalam romantisme yang simplistis. Dia membawa kita menyelami kompleksitas gerakan ini dengan mata kritis, penuh ketelitian, dan yang terpenting, dengan rasa hormat terhadap praktik di lapangan. Buku ini berhasil menjadi jembatan antara wacana akademis yang abstrak dengan realitas konkret di mana gagasan tentang hak alam diuji, diterapkan, dan kadang diperdebatkan.
Sebelum menyelami argumen utama Tănăsescu, penting untuk memahami titik berangkatnya. Selama ini, hukum lingkungan konvensional bersifat antroposenrik—berpusat pada manusia. Alam dilindungi sejauh ia memberikan “jasa ekosistem” bagi manusia. Hutan dilindungi karena menyerap karbon, sungai dijaga karena menjadi sumber air minum. Paradigma ini, meski telah berjasa, memiliki kelemahan fatal: alam hanya bernilai instrumental.
Tănăsescu dengan tegas membedakan Rights of Nature dari pendekatan ini. Hak alam menganut paham nilai intrinsik—alam memiliki nilai pada dirinya sendiri, terlepas dari kegunaannya bagi manusia. Pergeseran ini bukan sekadar perubahan semantik, melainkan revolusi filosofis.
“The difference is that in the case of rights of nature, the legal system is called upon to protect nature not for the benefit of humans, but for its own sake.” (Halaman 8)
Ini adalah terobosan konseptual yang mendasar. Ketika sebuah gunung atau danau diberikan hak, ia berubah statusnya dari “benda” menjadi “subjek hukum”. Ia memiliki legal standing—kapasitas untuk tampil di pengadilan. Tentu saja, alam tidak bisa berbicara sendiri. Di sinilah peran wali atau *guardianmuncul, mirip dengan wali hukum untuk anak di bawah umur atau orang dengan disabilitas mental. Guardian ini—bisa berupa komunitas adat, LSM, atau komisi khusus—yang akan bersuara mewakili kepentingan alam di hadapan hukum.
Menelusuri Jejak Hak-Hak Alam dalam Realitas: Ekuador, Selandia Baru, dan Kolumbia
Kekuatan utama buku Tănăsescu terletak pada komitmennya untuk membumikan teori. Dia tidak hanya berfilsafat di menara gading, tetapi meneliti dengan seksama bagaimana konsep hak alam ini hidup dan bernafas dalam konteks yang berbeda-beda.
1. Ekuador: Hak Alam dalam Konstitusi
Ekuador adalah negara pertama di dunia yang mencantumkan Hak Alam (Pacha Mama) dalam konstitusinya pada 2008. Pasal 71 Konstitusi Ekuador menyatakan: “Alam, atau Pacha Mama, di mana kehidupan bereproduksi dan terjadi, memiliki hak untuk dihormati secara utuh keberadaan dan pemeliharaan serta regenerasi siklus hidup, struktur, fungsi, dan proses evolusionernya.”
Tănăsescu menganalisis bagaimana pasal ini diterjemahkan ke dalam yurisprudensi. Dia mengkaji kasus sungai Vilcabamba, salah satu kasus pertama di mana hak alam digunakan secara sukses di pengadilan. Namun, analisisnya juga kritis. Dia menunjukkan bahwa meski memiliki landasan konstitusional yang kuat, implementasinya di Ekuador menghadapi tantangan besar dari paradigma pembangunan ekstraktif (pertambangan dan minyak) yang masih dominan. Hal ini menunjukkan bahwa hukum tertulis saja tidak cukup; diperlukan pergeseran kekuasaan dan politik yang mendalam.
2. Selandia Baru: Sebuah Perjanjian dengan Sungai
Mungkin contoh paling terkenal adalah pengakuan terhadap Sungai Whanganui di Selandia Baru sebagai entitas hidup yang memiliki hak pada 2017. Yang menarik dari analisis Tănăsescu adalah penelusurannya pada akar historis dan kultural dari keputusan ini. Pengakuan terhadap Sungai Whanganui bukanlah semata-mata inovasi hukum lingkungan modern, melainkan hasil dari perjuangan panjang selama 140 tahun oleh suku Māori, Iwi Whanganui.
Bagi Māori, sungai bukanlah “sumber daya”, melainkan leluhur (tupuna). Hubungan mereka dengan sungai adalah hubungan kekerabatan, yang diungkapkan dalam pepatah “Ko au te awa, ko te awa ko au” (Aku adalah sungai, dan sungai adalah aku). Tănăsescu berargumen bahwa kesuksesan relatif model Selandia Baru terletak pada fakta bahwa hak hukum tersebut dibangun di atas fondasi ontologi (cara memahami realitas) yang sudah hidup dan dipegang teguh oleh komunitas.
“The constitutional recognition of nature’s rights in Ecuador is a monumental achievement, but it exists in tension with a state apparatus still heavily reliant on extractive industries. This creates a sort of legal schizophrenia.” (Halaman 45)
“The Whanganui River settlement is significant precisely because it does not simply impose a Western legal concept onto an indigenous reality. Instead, it allows the Māori worldview to reshape the law itself.” (Halaman 88)
Di sini, hukum common law Barat “dibajak” untuk melayani cara pandang yang sama sekali berbeda. Dua guardian ditunjuk untuk mewakili sungai: satu dari masyarakat Māori, satu dari pemerintah, mencerminkan perwalian bersama.
3. Kolumbia: Hak Alam melalui Yudisial
Sementara Ekuador melakukannya melalui konstitusi dan Selandia Baru melalui perundang-undangan, di Kolumbia, hak alam justru muncul dari putusan-putusan pengadilan yang progresif. Mahkamah Agung Kolumbia pada 2016 mengakui Sungai Atrato sebagai entitas subjek hak, dan kemudian pada 2018, Mahkamah Agung mengakui kawasan Amazon Kolumbia sebagai entitas yang memiliki hak.
Tănăsescu melihat fenomena ini sebagai bentuk “aktivisme hakim” yang merespons krisis ekologis yang akut. Putusan-putusan ini seringkali menggunakan bahasa yang puitis dan filosofis, menyatakan bahwa alam adalah “subjek hak yang tidak dapat diganggu gugat” dan bahwa negara memiliki tugas untuk melindunginya. Namun, dia juga mempertanyakan efektivitasnya. Tanpa infrastruktur politik dan sosial yang memadai untuk menjalankan perwalian dan memaksa pemerintah bertindak, putusan yang visioner bisa mandek di atas kertas.
Kritik dan Kompleksitas: Menghadapi Pertanyaan-Pertanyaan Sulit
Buku Tănăsescu sangat berharga justru karena ia tidak menghindari kritik dan pertanyaan-pertanyaan sulit. Dia dengan jeli mengidentifikasi beberapa jebakan dan tantangan dalam gerakan Rights of Nature:
1. Problematika Perwakilan (The Problem of Representation): Siapa yang berhak menjadi “suara” alam? Bagaimana kita memastikan bahwa guardian benar-benar mewakili kepentingan sungai, dan bukan kepentingan politik atau ekonominya sendiri? Tănăsescu memperingatkan bahwa konsep perwalian bisa terjerumus ke dalam model paternalistik yang justru mengulangi logika dominasi, meski dengan wajah yang lebih ramah.
“The question of who speaks for nature is perhaps the most difficult political question that the rights of nature movement must confront. Without a clear and accountable theory of representation, the rights of nature risk becoming another tool for powerful human interests.”(Halaman 124)
2. Antroposentrisme yang Menyusup Kembali (The Reinscription of Anthropocentrism): Apakah dengan memberikan “hak” kepada alam—sebuah konsep yang sangat manusiawi dan Barat—kita justru memaksakan kerangka pikir kita sendiri kepada alam? Bukankah ini cara lain untuk mengasimilasi alam ke dalam dunia manusia, alih-alih membiarkannya menjadi “liar” dan “lain”? Tănăsescu mengakui dilema ini. Di satu sisi, menggunakan bahasa hukum adalah strategi pragmatis. Di sisi lain, ada risiko kehilangan esensi radikal dari gagasan untuk mengakui “otherness” (keliaran) alam.
3. Konflik antara Hak: Bagaimana jika hak sebuah hutan untuk beregenerasi bertabrakan dengan hak manusia untuk mencari nafkah? Atau hak sungai untuk mengalir bebas bertabrakan dengan hak komunitas untuk membangun bendungan untuk irigasi? Tănăsescu berargumen bahwa hak alam bukanlah pedang yang memotong semua masalah. Ia justru memerlukan politik deliberatif yang lebih dalam, di mana berbagai kepentingan—manusia dan non-manusia—harus didengarkan dan ditimbang. Hukum bukanlah solusi akhir, melainkan panggung bagi pertarungan politik dan etika yang berkelanjutan.
Sebuah Pergeseran Paradigma yang Menjanjikan
Setelah menuntun pembaca melalui berbagai studi kasus dan kritik yang mendalam, Tănăsescu sampai pada kesimpulan yang nuanced dan penuh harap. Rights of Nature, baginya, bukanlah solusi ajaib yang akan menyelesaikan krisis ekologis dalam semalam. Ia adalah sebuah alat politik dan hukum yang powerful yang membuka kemungkinan untuk berpikir dan bertindak secara berbeda.
Kekuatan sejatinya terletak pada kemampuannya untuk mengganggu (disrupt) cara-cara biasa kita dalam berhubungan dengan dunia. Dengan mengakui subjektivitas hukum alam, kita dipaksa untuk mempertanyakan asumsi dasar tentang dominasi manusia.
“The rights of nature are not a silver bullet. They are, rather, a profound legal and political experiment that has the potential to reshape our imagination of what is possible in the relationship between human societies and the living world.” (Halaman 192)
Buku ini pada akhirnya adalah undangan untuk membayangkan ulang dunia. Dunia di mana kita bukanlah penguasa yang terpisah dari alam, melainkan bagian yang terintegrasi dalam jaring-jaring kehidupan yang kompleks. Sebuah dunia diaimana kerusakan terhadap sebuah sungai dilihat bukan sebagai “kerusakan properti”, melainkan sebagai “pelanggaran hak”, sebuah kesalahan terhadap seorang rekan penghuni planet ini.
Catatan Penutup
Membaca buku Tănăsescu, pikiran kita tak bisa tidak melayang ke konteks Indonesia. Bagaimana gagasan ini bisa ber resonansi di negeri dengan kekayaan alam dan keragaman budaya adat yang luar biasa ini?
Konsep “hak alam” sebenarnya bukanlah hal yang asing. Filsafat hidup banyak komunitas adat di Nusantara sudah mencerminkan hal ini. Dari masyarakat Dayak dengan konsep “pancasila alam”, hingga masyarakat Bali dengan filosofi “Tri Hita Karana” yang menekankan harmoni dengan alam, hingga berbagai kepercayaan tentang penunggu hutan dan sungai yang mensakralkan alam. Dalam banyak hal, gerakan Rights of Nature di tingkat global adalah semacam pengakuan kembali terhadap kearifan lokal yang telah lama dipinggirkan oleh hukum negara modern.
Bayangkan jika Sungai Citarum, yang telah menjadi simbol krisis polusi terparah, diberikan status sebagai subjek hak. Bukan hanya untuk “manfaat” bagi warga Jakarta dan Bandung, tetapi karena Sungai Citarum sendiri memiliki hak untuk hidup, untuk diselamatkan dari kematian. Bayangkan jika guardian yang terdiri dari perwakilan masyarakat adat, ilmuwan, dan aktivis lingkungan diberikan mandat untuk menggugat para pencemar dan memaksa negara membersihkannya.
Tentu, jalan menuju sana penuh dengan tantangan, sebagaimana diingatkan oleh Tănăsescu. Kekuatan korporasi, mentalitas ekstraktif dalam kebijakan, dan kompleksitas representasi adalah rintangan nyata. Namun, buku ini memberikan kita peta dan kompas untuk memulai perjalanan itu.
“Understanding the Rights of Nature” oleh Mihnea Tănăsescu adalah bacaan wajib bagi siapa saja yang peduli pada masa depan planet kita—mulai dari aktivis, pengacara, pembuat kebijakan, akademisi, hingga masyarakat umum. Buku ini tidak menawarkan jawaban yang mudah, tetapi ia memberikan pertanyaan-pertanyaan yang tepat. Dan dalam era krisis ekologis yang kita hadapi sekarang, bertanya dengan tepat adalah langkah pertama yang paling penting menuju perubahan. Buku ini adalah suara yang jelas, kritis, dan sangat dibutuhkan dalam percakapan global tentang bagaimana kita bisa belajar untuk tidak hanya tinggal di Bumi, tetapi juga untuk menjadi mitra yang setara dengan segala kehidupan di dalamnya.