Ekonomi Politik Tembakau: Mobilisasi Sumber Daya dalam Perlawanan Petani 
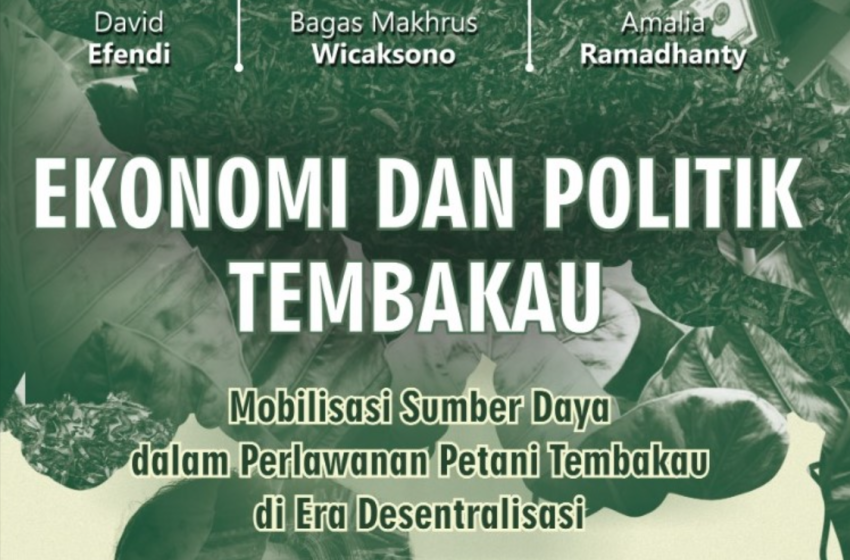
Buku ini memotret ekonomi politik pertembakauan di Temanggung dengan tiga fokus utama: (1) bagaimana implementasi SK Bupati 510/369/2019 tentang pembentukan Gugus Tugas Pertembakauan; (2) faktor pendukung dan penghambat pelaksanaannya; serta (3) bentuk mobilisasi APTI dalam memperjuangkan hak-hak petani tembakau. Fokus ini ditegaskan sejak awal sebagai upaya menambah khazanah ilmu dan menjadi rujukan analisis gerakan sosial petani tembakau, khususnya di Temanggung (hlm. 23–24).
Dalam Bab II disediakan landasan teoritis mengenai kebijakan publik dan implementasinya, desentralisasi untuk pengelolaan sumber daya, pemberdayaan ekonomi masyarakat, serta gerakan sosial (hlm. 41–65). Kerangka ini menjadi perangkat analitis untuk membaca dinamika kebijakan tembakau dan strategi kolektif petani di ranah lokal.
Konteks Temanggung, tata niaga, dan pembentukan Gugus Tugas
Buku menegaskan Temanggung sebagai “Kota Tembakau”, pemasok tembakau lauk yang dibutuhkan semua pabrikan kretek karena aroma dan kadar nikotinnya (3–8%) (hlm. 4–5). Namun relasi dagang historis antara petani dan gudang/pabrikan bersifat eksploitatif: penentuan kualitas, harga, dan timbangan didominasi pengepul/juragan (hlm. 5).
Untuk memperbaiki koordinasi pasar sekaligus mengawal panen raya, Pemkab Temanggung membentuk Gugus Tugas Pertembakauan melalui SK Bupati 510/369/2019 (28 Agustus 2019). Struktur organisasi menempatkan Bupati sebagai pengarah, Wakil Bupati dan Staf Ahli Ekonomi sebagai pembina, serta Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda sebagai ketua. Bidangnya meliputi budidaya, industri dan perdagangan, humas, aduan masyarakat, lobi dan negosiasi (hlm. 77–78; 93–95).
Tugas formal gugus tugas meliputi pemantauan harga harian; koordinasi dengan camat/kepala desa; pelaporan permasalahan; dan antisipasi hal yang tidak diinginkan—semuanya bertanggung jawab ke Bupati (hlm. 94–95).
Evaluasi awal (musim panen 2019) menunjukkan panen terserap penuh oleh pabrikan karena kualitas baik; Gudang Garam dan Djarum bahkan menyerap di atas tonase tahunan resmi. Namun tim menilai perlu penguatan peran dan personel, termasuk rencana Perda Pertembakauan (hlm. 101–104).
Di sisi tata niaga, buku menggambarkan rantai panjang: petani kecil jarang menjual langsung ke bakul/tengkulak ber-KTA; muncul calo; Temanggung menjadi pasar bebas di mana tembakau luar daerah (“temanggungngan”) masuk; gudang Gudang Garam membeli di atas kuota wilayah (hlm. 157–158; 171). Konsekuensinya, tata niaga menjadi persoalan utama kedua setelah regulasi pusat (PP 109/2012; PMK 222/2017; PMK 152/2019) (hlm. 158; 171).
Bantuan DBH CHT via Dinas Pertanian sebagai input (pupuk), tetapi pascapanen petani tetap kesulitan menjual karena kuota pabrikan dipenuhi para pemain tertentu; harga yang semestinya 700–750 ribu/kg (2014) tinggal ~400 ribu (2019). APTI dipandang belum banyak masuk ke pembenahan rantai niaga (hlm. 183).
Politik desentralisasi: peluang dan batas
Secara konseptual, buku memaknai desentralisasi sebagai otonomisasi masyarakat wilayah; pelimpahan kewenangan dari pusat ke daerah guna memperluas jangkauan pelayanan publik, memperkuat representasi politik, dan mendorong inovasi pemerintah–swasta–organisasi masyarakat (hlm. 49–50).
Namun penulis juga mengingatkan risiko fragmentasi dalam implementasi kebijakan: semakin banyak unit birokrasi terlibat, semakin tinggi biaya koordinasi dan semakin kecil peluang sukses implementasi (hlm. 48–49).
Bukti empirisnya terlihat pada Gugus Tugas. Pertama, struktur yang didominasi pejabat eselon dan camat dinilai kurang cocok untuk kerja-kerja lapangan analitis di tingkat petani; idealnya melibatkan praktisi pertanian (Dinas Pertanian) dan organisasi masyarakat (hlm. 103–104). Kedua, tanpa regulasi daerah tentang tata niaga—misalnya Perda—kewenangan tim lemah, sehingga kinerjanya mudah “macet” pasca-musim panen (hlm. 103).
Di sini tampak paradoks desentralisasi: ruang kebijakan lokal hadir (pembentukan tim, wacana Perda), tetapi ketergantungan pada regulasi pusat (cukai, KTR, impor) dan realitas pasar oligopsoni membuat intervensi lokal terbatas daya pengungkitnya. Argumentasi buku mengenai SOP/fragmentasi birokrasi memperkuat analisis ini (hlm. 48–49).
Regulasi nasional sebagai akar resistensi
Bab V memetakan regulasi yang menjadi akar perlawanan petani: PP 109/2012 (pengamanan zat adiktif tembakau), tarik ulur dengan FCTC, dan dua PMK kunci 222/2017 (DBH CHT) dan 152/2019 (kenaikan cukai). Buku menggarisbawahi kemiripan substansi PP 109/2012 dengan FCTC (mis. pasal KTR dan pelabelan) dan menilai kemunculan regulasi itu sebagai respons terhadap tekanan global yang berdampak pada kedaulatan politik pertembakauan (hlm. 10; 128–130).
Terkait DBH CHT, PMK 222/2017 mensyaratkan ≥50% dialokasikan untuk mendukung JKN, sehingga porsi yang kembali ke hulu terasa kecil (hlm. 15). Data nasional 2018 menunjukkan hanya ±9,27% untuk “peningkatan kualitas bahan baku”; selebihnya didominasi pembinaan lingkungan sosial (88,14%) (hlm. 147–148). Kritik buku: dana cukai yang berasal dari ekosistem tembakau semestinya lebih kuat menopang petani/buruh dan keberlangsungan kretek, bukan dimonopoli untuk kesehatan semata (hlm. 148).
Sementara PMK 152/2019 dipotret berdampak ganda: (i) menggeser psikologi harga rokok (melewati ambang Rp16.000) sehingga konsumsi turun/pindah merek/linting sendiri; (ii) menurunkan serapan bahan baku lokal dan mendorong pabrikan beralih ke tembakau impor karena kepraktisan pasokan dan skema pembayaran (hlm. 153–154).
APTI sebagai gerakan sosial: mobilisasi sumber daya dan “keterlibatan kritis”
Buku merekonstruksi APTI sebagai wadah gerakan sosial petani tembakau. Secara normatif, gerakan sosial muncul ketika sistem tidak menjawab problem publik; civil society berperan mengawasi kekuasaan (hlm. 169–170). Di Temanggung, APTI—berakar dari Paguyuban Petani Tembakau Sindoro-Sumbing—mencatat capaian historis: mengawal perubahan PP 81/1999 menjadi PP 19/2003 yang dinilai lebih adil; dan saat ini fokus pada dampak kapitalisasi global dan regulasi anti-tembakau (hlm. 169–170).
Secara taktis, buku menginventarisasi rangkaian aksi APTI: audiensi ke DPR RI (16/11/2016), aksi di Semarang (9/1/2017), doa bersama dan baliho tuntutan RUU Pertembakauan (17/3/2017), hingga aksi damai di depan Istana menolak kenaikan cukai (24/10/2019). Semua menunjukkan kesinambungan protest politics di tingkat nasional/regional (hlm. 21–22).
Pada November 2019, APTI juga memadukan information politics melalui rapat pimpinan nasional membahas dampak PMK 152/2019, menghadirkan Gubernur, perwakilan Bea Cukai dan Kementan (hlm. 178–179). Di saat bersamaan, aksi lokal menolak KTR di Temanggung mengiringi kunjungan Kemenko PMK—Bupati menyatakan perda KTR belum akan diwujudkan dengan alasan Temanggung daerah penghasil tembakau (hlm. 171).
Buku juga menyinggung Laskar Kretek (deklarasi 2012 di Temanggung) sebagai mitra pergerakan yang mengonsolidasikan unsur pemuda—keduanya kerap bertindak sebagai satu kesatuan dalam aksi massa (hlm. 174–176). Peran kepemimpinan (DPN APTI, ketua APTI Jateng, pendiri Laskar Kretek) dilukiskan sebagai “ujung tombak” yang mengartikulasikan aspirasi ke eksekutif pusat (mis. Majelis bertemu Presiden/menteri terkait) (hlm. 174–176).
Menariknya, APTI mengadopsi strategi “keterlibatan kritis” di ranah elektoral: tidak menutup diri pada politik praktis, tetapi menggunakan momentum pilkada/pileg/pilpres untuk membangun kanal advokasi; dukungan diberikan pada kandidat yang dianggap pro-tembakau, sembari menegaskan batas normatif tertentu (hlm. 176).
Kesesuaian dengan teori gerakan sosial
Landasan teoretis yang digunakan penulis—khususnya teori mobilisasi sumber daya—diturunkan secara eksplisit: organisasi, kepemimpinan, sumber daya (moral, kultural, organisasi, manusia, material), jaringan/partisipasi, serta peluang dan kapasitas masyarakat sebagai faktor determinan gerakan (hlm. 60–62). Narasi empiris APTI sangat koheren dengan daftar determinan ini: ada organisasi formal (APTI/Laskar), kepemimpinan yang menonjol, jaringan lintas wilayah, hingga kemampuan memadukan aksi jalanan, lobi, dan produksi wacana (hlm. 60–62; 168–176).
Penilaian kritis
Kekuatan utama buku ini terletak pada (a) integrasi level analisis: dari kebijakan nasional (PP 109, PMK 222, PMK 152) ke desentralisasi kabupaten (Gugus Tugas) dan ke praktik mikro tata niaga; (b) koherensi teoritis antara kerangka mobilisasi sumber daya dan praktik APTI; (c) kaya data empiris yang menautkan narasi kebijakan dengan suara pelaku lapangan—misalnya potret pasar bebas tembakau “temanggungngan” dan testimoni petani soal kuota pabrikan (hlm. 157–158; 183).
Kontribusi khas buku ini terhadap studi ekonomi politik pertanian adalah penekanan pada “simetri ketidakseimbangan” antara desentralisasi (yang memberi ruang inovasi lokal) dan kebijakan pusat (yang mengunci struktur insentif). Wacana Perda Pertembakauan menunjukkan bahwa otonomi memberi peluang, tetapi keberhasilan implementasi terganjal fragmentasi birokrasi dan ketiadaan local enabling regulation (hlm. 48–50; 101–104).
Pada saat yang sama, buku memberikan evaluasi tajam atas penyaluran DBH CHT: desain alokasi yang memprioritaskan JKN (≥50%) dan realisasi 2018 yang berat ke “pembinaan lingkungan sosial” membuat porsi ke hulu (kualitas bahan baku, pembinaan industri) relatif kecil (hlm. 15; 147–148). Ini menyodorkan agenda riset/advokasi lanjutan: bagaimana mendesain mekanisme earmarking yang lebih adil bagi petani/buruh (hlm. 148).
Keterbatasan buku ini setidaknya ada terutama dua. Pertama, narasi tata niaga masih bertumpu pada deskripsi rantai dan testimoni, sementara analitik struktur pasar (mis. derajat konsentrasi grader/pabrikan, perilaku kuota, dan dinamika harga lintas musim) bisa diperkuat dengan data kuantitatif berjenjang. Kedua, analisis policy designdi level kabupaten (mis. prototipe Perda) dapat diperluas ke instrumen yang secara konkret menyeimbangkan posisi tawar petani: standardisasi grade berbasis third-party inspection, koperasi pemasaran, atau floor price berbasis kualitas. Meski begitu, diagnosis buku sudah tajam: tim gugus tanpa dukungan regulasi tata niaga tidak efektif (hlm. 103).
Aspek politik desentralisasi: simpul argumen
Buku berhasil menunjukkan bahwa desentralisasi bukan otomatis pro-petani. Ia menyediakan ruang institusional (SK gugus tugas, wacana Perda) dan kapasitas koordinasi (pemantauan harga, sosialisasi budidaya), tetapi problem struktur pasar dan ketergantungan regulasi pusat membatasi daya ubah kebijakan lokal. Penulis menyodorkan peringatan implementasi: SOP dan fragmentasi memperkecil peluang keberhasilan bila lintas-OPD tak solid, dan bila anggota tim adalah pejabat eselon dengan keterbatasan kerja lapangan (hlm. 48–49; 103–104).
Pada akhirnya, politik desentralisasi yang efektif mensyaratkan koherensi vertikal (sinkronisasi regulasi pusat–daerah) dan koherensi horizontal (koordinasi intra-daerah plus kemitraan dengan civil society). Kasus Temanggung memperlihatkan keduanya masih proses—dan buku ini menyediakan peta rute untuk perbaikannya.
Aspek gerakan sosial APTI: dari mobilisasi ke advokasi berjejaring
Dengan mengadopsi lensa mobilisasi sumber daya, buku memperlihatkan bagaimana APTI mengonversi aset organisasi–kepemimpinan–jaringan menjadi daya tekan. Ini terlihat pada rangkaian aksi protes (2016–2019), lobi nasional (RAPIMNAS 2019), pengelolaan aliansi (Laskar Kretek), dan keterlibatan kritis di kontestasi elektoral (hlm. 21–22; 174–176; 178–179). Di sisi wacana, APTI juga mengartikulasikan kritik kebijakan yang konsisten (PP 109, KTR, PMK 152) hingga memengaruhi keputusan lokal—misalnya komitmen Bupati untuk tidak mewujudkan perda KTR (hlm. 171).
Secara teoretis, APTI dalam resource mobilization menjadi faktor determinan yang dirumuskan penulis (organisasi, pimpinan, sumber daya, jaringan, peluang) tampak dalam praktik APTI (hlm. 60–62). Kehadiran figur pemimpin (DPN APTI, ketum Jateng, pendiri Laskar Kretek) menjadi “kaum profesional gerakan” yang mampu memobilisasi sumber daya, menavigasi relasi dengan elite, dan mengelola media (hlm. 60–62; 174–176).
Sebagai studi kasus ekonomi politik pertembakauan di era desentralisasi, buku ini menawarkan sintesis penting antara institusi lokal (Gugus Tugas) dan gerakan sosial (APTI) sama-sama krusial, tetapi bekerja di medan struktural yang dibentuk regulasi nasional dan struktur pasar. Para penulis menunjukkan bahwa pemberdayaan petani tak cukup lewat teknis budidaya; ia memerlukan koreksi tata niaga, desain DBH CHT yang adil, dan sinkronisasi kebijakan lintas level. Di sisi gerakan, APTI dipotret efektif dalam protest/information politics dan artikulasi isu, sembari terus mencari strategi memperkuat posisi tawar di hulu rantai nilai.