Review Buku “The Narrow Corridor: States, Societies, and the Fate of Liberty”
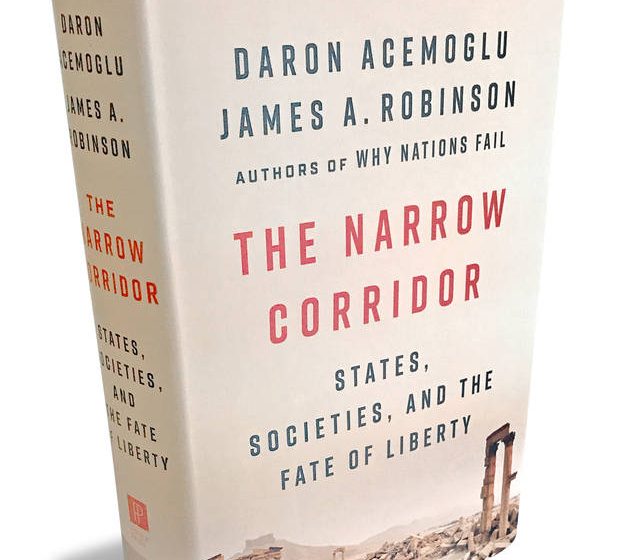
Sumber: wsj.com
Buku ini ditulis oleh Daron Acemoglu, ekonom terkemuka dari Massachusetts Institute of Technology (MIT), dan James A. Robinson, ilmuwan politik dari University of Chicago yang kini aktif di University of Chicago’s Pearson Institute. Keduanya dikenal luas melalui karya monumental Why Nations Fail (2012) yang menekankan peran institusi politik dalam menjelaskan kemajuan atau kemunduran bangsa. The Narrow Corridor diterbitkan pada 2019 oleh Penguin Press, sebagai upaya melanjutkan dan memperdalam tesis mereka mengenai hubungan antara negara, masyarakat, dan kebebasan. Konteks kelahiran buku ini tidak lepas dari kegelisahan akademik sekaligus realitas politik global: meningkatnya otoritarianisme, kegagalan negara di Timur Tengah dan Afrika, serta munculnya pertanyaan baru tentang masa depan demokrasi dalam era digital dan globalisasi.
Sejak kata pengantar, penulis menegaskan bahwa buku ini berbicara tentang liberty atau kebebasan yang dipahami bukan sekadar absennya kekuasaan, tetapi kondisi di mana masyarakat terbebas dari dominasi, ketakutan, dan kekerasan, sebagaimana didefinisikan John Locke dan kemudian diformulasikan ulang oleh Philip Pettit dalam gagasan non-dominance.
Pokok argumentasi buku ini adalah bahwa kebebasan tidak lahir dari ketiadaan negara, juga tidak muncul dari negara yang terlalu dominan, melainkan dari kondisi unik di mana negara kuat dan masyarakat kuat saling mengimbangi. Ruang keseimbangan ini mereka sebut sebagai the narrow corridor yakni koridor sempit yang memungkinkan kebebasan tumbuh. Di luar koridor tersebut, masyarakat jatuh ke dalam dua ekstrem:
- Despotik Leviathan – negara terlalu kuat, menindas, dan mengabaikan aspirasi masyarakat (contoh: Nazi Jerman, Tiongkok era Mao, Suriah di bawah Assad).
- Absent Leviathan – negara lemah atau runtuh, menghasilkan anarki, kekerasan, dan ketidakamanan (contoh: Kongo, Somalia, atau Suriah pasca-perang saudara).
Narasi historis dan antropologis digunakan secara ekstensif untuk mendukung argumen ini. Acemoglu & Robinson memulai dari kisah mitologis Gilgamesh untuk menggambarkan “masalah Gilgamesh”: bagaimana mengendalikan penguasa agar negara memberi manfaat, bukan menindas rakyat. Mereka kemudian menelusuri kasus-kasus kontemporer: kegagalan negara di Suriah, anarki di Nigeria, hingga otoritarianisme modern.
Metode yang dipakai lebih bersifat komparatif-historis dengan pendekatan lintas disiplin: ekonomi politik, sosiologi, filsafat politik, dan antropologi. Gaya penulisan mereka naratif, kaya ilustrasi empiris, namun tetap analitis dengan upaya menyajikan teori besar yang mudah dicerna pembaca umum maupun akademisi.
Dalam konteks akademik, buku ini memperkaya studi mengenai negara, demokrasi, dan pembangunan dengan menawarkan kerangka konseptual baru: koridor sempit. Ia mengoreksi pandangan deterministik yang cenderung melihat negara kuat sebagai jaminan kebebasan (ala Hobbes) atau sebaliknya mendorong pelemahan negara demi otonomi masyarakat. Relevansi praktisnya sangat besar bagi negara-negara berkembang, termasuk Indonesia, yang menghadapi tantangan menjaga keseimbangan antara peran negara dalam pembangunan dan partisipasi masyarakat sipil. Buku ini juga relevan dalam membaca fenomena populisme global, otoritarianisme digital, dan krisis legitimasi demokrasi.
Secara kritis, buku ini sangat inspiratif, tetapi juga menghadapi beberapa keterbatasan. Pertama, kerangka narrow corridor cenderung normatif, tanpa selalu memberikan ukuran operasional yang jelas kapan suatu negara “berada di dalam koridor”. Kedua, kasus-kasus yang diangkat sering kali berfokus pada Eropa dan negara-negara besar, sementara kompleksitas lokal di Asia Tenggara atau Amerika Latin hanya disinggung sekilas. Meski begitu, validitas argumennya tetap kuat karena berbasis pada pola historis yang konsisten: kebebasan tidak pernah diberikan dari atas, tetapi diambil dan dijaga melalui mobilisasi masyarakat.
Secara pribadi, saya memetik pelajaran penting bahwa liberty adalah proses, bukan produk final. Kebebasan bukan hadiah dari negara atau elite, melainkan hasil perjuangan terus-menerus masyarakat dalam mengontrol negara. Refleksi ini memperkaya pemahaman saya bahwa demokrasi tidak boleh dipandang sebagai sesuatu yang statis atau otomatis lestari, melainkan ruang sempit yang harus dipelihara melalui partisipasi, protes, dan konsolidasi masyarakat sipil.
Dalam konteks Indonesia, buku The Narrow Corridor memberikan perspektif yang tajam untuk membaca pengalaman Indonesia sejak Reformasi 1998. Jika menggunakan kerangka Acemoglu & Robinson, dapat dikatakan bahwa Indonesia sejak jatuhnya Orde Baru mencoba masuk ke dalam koridor sempit kebebasan. Reformasi berhasil melemahkan Leviathan yang sebelumnya sangat despotik ditandai dengan dominasi negara atas masyarakat, represi politik, dan terbatasnya ruang sipil. Namun, pasca-Reformasi, tantangan baru muncul: bagaimana membangun negara yang tetap kuat dalam menyediakan hukum, layanan publik, dan stabilitas, tanpa jatuh kembali ke dalam otoritarianisme.
Fenomena politik Indonesia mutakhir menunjukkan dinamika keluar-masuk dari koridor ini. Di satu sisi, kebebasan sipil relatif lebih terjamin dibanding era sebelumnya; pers bebas, partai politik beragam, dan masyarakat sipil cukup aktif. Namun di sisi lain, gejala despotic Leviathan masih tampak dalam bentuk pelemahan lembaga-lembaga pengawas seperti KPK, pembatasan kebebasan berekspresi melalui pasal karet, serta kedekatan oligarki dengan struktur politik yang membuat masyarakat sulit mengendalikan negara.
Sebaliknya, Indonesia juga berhadapan dengan ancaman absent Leviathan pada level lokal, misalnya lemahnya penegakan hukum di daerah, praktik korupsi yang merajalela, serta ketidakmampuan negara dalam menjawab krisis lingkungan atau konflik sosial. Dalam kasus ini, negara tampak tidak hadir, sehingga masyarakat “dipaksa” mencari cara sendiri untuk bertahan, mirip dengan ilustrasi “Débrouillez-vous” di Kongo yang digambarkan dalam buku.
Refleksi pribadi saya adalah bahwa pelajaran dari Acemoglu & Robinson relevan untuk mengingatkan bahwa demokrasi Indonesia bukanlah hasil akhir dari Reformasi, melainkan proses yang terus berjalan. Kebebasan hanya dapat bertahan jika masyarakat sipil terus waspada, mengorganisir diri, dan menuntut akuntabilitas negara. Tanpa itu, Indonesia berisiko keluar dari koridor sempit menuju dua kutub ekstrem: kembali ke despotisme atau jatuh ke dalam kelemahan negara yang melahirkan ketidakadilan.
Secara keseluruhan, The Narrow Corridor merupakan kontribusi penting dalam studi politik dan ekonomi dengan menawarkan kerangka baru tentang relasi antara negara dan masyarakat. Ia mengingatkan bahwa jalan menuju kebebasan selalu sempit dan rapuh, membutuhkan keseimbangan dinamis antara kekuatan negara dan kekuatan masyarakat. Bagi akademisi, buku ini memperkaya analisis teoritis tentang demokrasi dan negara, bagi praktisi maupun warga negara, ia menjadi pengingat bahwa menjaga kebebasan menuntut kewaspadaan dan keterlibatan aktif setiap hari.